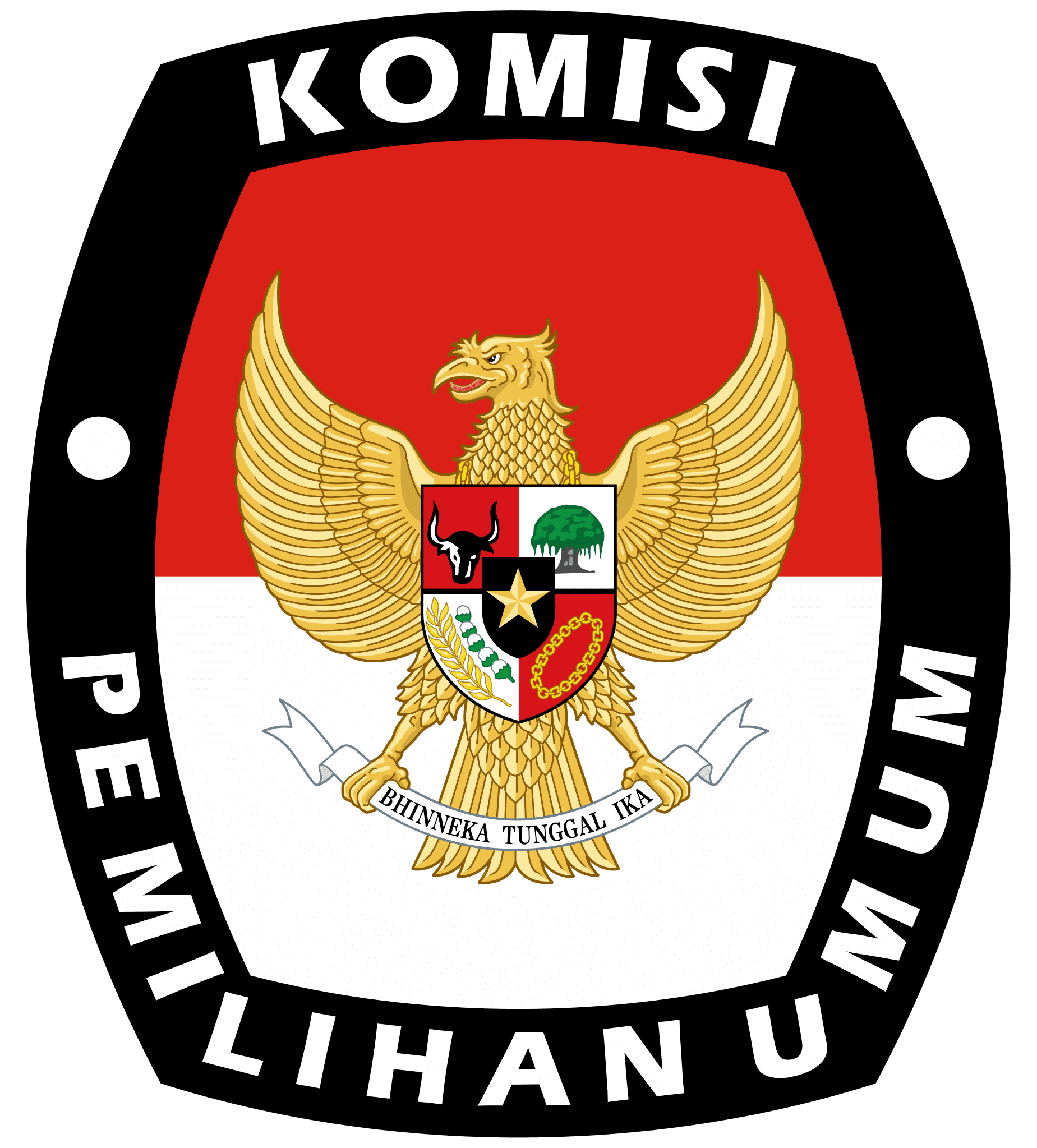KPU Bone Bolango Jalin Koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk Sosialisasi Pendidikan Pemilih
#TemanPemilih, Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Idris Djou, yang didampingi Kepala Subbagian SDM Fahmy Djibran serta staf sekretariat, melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bone Bolango, dalam rangka membahas rencana sosialisasi pendidikan pemilih, Rabu 07/01/2026. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Darlinawaty M. Djafar, di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bone Bolango. Koordinasi ini dilakukan sebagai upaya KPU untuk memperluas jangkauan pendidikan pemilih, khususnya kepada kelompok masyarakat marjinal. Dalam kesempatan tersebut, Idris Djou menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Bone Bolango berencana menggelar sosialisasi pendidikan pemilih yang menyasar segmen petani. Menurutnya, petani merupakan salah satu kelompok strategis yang perlu mendapatkan pemahaman kepemiluan secara berkelanjutan. “Kegiatan sosialisasi ini rencananya akan dilaksanakan dengan cara bergabung atau kolaborasi dengan dinas pertanian pada kegiatan penyuluhan pertanian yang sudah terjadwal".ujar Idris. Melalui koordinasi ini, KPU Kabupaten Bone Bolango berharap pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih kepada para petani dapat berjalan optimal serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas partisipasi pemilih di daerah. #KPUMelayani ....

Pengumuman Hasil Pemutakhiran Data Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester II Tahun 2025
Hai #TemanPemilih, berdasarkan hasil verifikasi terhadap data dan dokumen pemutakhiran Partai Politik dengan ini kami sampaikan Pengumuman Hasil Pemutakhiran Data Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester II Tahun 2025, silahkan Klik DISINI untuk melihat hasilnya yaa. ....

KPU Bone Bolango Laksanakan Rakor Evaluasi PDPB Tahun 2025 dan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui SIPOL
#TemanPemilih, KPU Kabupaten Bone Bolango melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 serta Sosialisasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Kamis (18/12/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Polres Bone Bolango, Dandim 1304, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta perwakilan partai politik. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango, Sutenty Lamuhu, menyampaikan bahwa terdapat tiga tahapan teknis non-tahapan pemilu yang diinstruksikan oleh KPU RI dan dilaksanakan oleh KPU Bone Bolango, yakni Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), pemutakhiran data partai politik, serta sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kegiatan ini menjadi ruang evaluasi dan koordinasi atas pelaksanaan ketiga tahapan tersebut, sekaligus untuk menghimpun masukan terkait strategi ke depan agar informasi kepemiluan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini juga didukung oleh hibah non-tahapan dari Pemerintah Daerah sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan demokrasi. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Bone Bolango, Adnan A. Berahim, menjelaskan bahwa pemutakhiran data pemilih mengacu pada DPT terakhir yang ditetapkan pada pelaksanaan Pilkada dan dilakukan secara berkala setiap triwulan melalui coklit terbatas. Proses ini turut melibatkan partisipasi masyarakat melalui Huyula (himbauan layanan sukarela), di mana masyarakat dapat melaporkan data pemilih yang perlu dimutakhirkan sebagai bentuk sinergi antara KPU dan masyarakat. Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Shaqti Qhalbudien Yusuf, menambahkan bahwa pemutakhiran data partai politik dilaksanakan setiap semester. Hal ini penting untuk memastikan keakuratan data kepengurusan, keterwakilan perempuan minimal 30 persen, keanggotaan, serta keberadaan sekretariat partai politik. Melalui pemutakhiran ini, KPU berkomitmen menjaga keterbukaan dan transparansi sebagai bagian dari penguatan kelembagaan demokrasi. #KPUMelayani ....

KPU Kabupaten Bone Bolango menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penyusunan Surat Keputusan serta Pembuatan Abstrak Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDI
KPU Kabupaten Bone Bolango menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penyusunan Surat Keputusan serta Pembuatan Abstrak Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pada Jumat (12/12/2025). Kegiatan ini di ikuti oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Bone Bolango dan menghadirkan narasumber dari KPU Provinsi Gorontalo. Dalam sambutannya, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Gorontalo, Risan Pakaya, memberikan apresiasi kepada JDIH KPU Bone Bolango yang berhasil meraih Juara 1 pada penilaian JDIH tingkat provinsi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara komisioner dan sekretariat dalam menjalankan tugas kelembagaan. “Materi ini sangat penting. Karena itu, saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti dengan serius,” ujarnya. Sementara itu, Ketua KPU Bone Bolango, Sutenty Lamuhu, menyampaikan terima kasih kepada KPU Provinsi Gorontalo yang telah meluangkan waktu untuk memberikan Bimbingan Teknis. Ia juga mengapresiasi jajaran sekretariat yang selalu memberikan pelayanan terbaik dalam setiap penyelenggaraan kegiatan teknis KPU. Senada dengan itu, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas, Hukum dan SDM Muthia Usman KPU Provinsi Gorontalo, turut mengapresiasi KPU Bone Bolango sebagai instansi pertama yang melaksanakan kegiatan bimbingan teknis terkait peningkatan kapasitas penyusunan SK dan abstrak JDIH di lingkungan KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Gorontalo. Dengan adanya kegiatan ini, KPU Bone Bolango berharap kualitas pengelolaan dokumen hukum semakin meningkat serta mampu mendukung kinerja kelembagaan secara profesional dan akuntabel. ....

KPU Kabupaten Bone Bolango menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025 Tingkat Provinsi Gorontalo
#TemanPemilih, Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango Sutenty Lamuhu dan Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango Divisi Perencanaan Data dan Informasi Adnan A. Berahim yang didampingi Kasubbag Rendatin serta Operator Sidalih KPU Kab. Bone Bolango menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025 Tingkat Provinsi Gorontalo yang digelar KPU Provinsi Gorontalo pada Kamis (11/12/2025) di Aula KPU Provinsi. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Gorontalo Sophian Rahmola bersama para anggota, serta diikuti oleh Bawaslu Provinsi, Dukcapil, Korem 133, Polda Gorontalo, Kanwil Pemasyarakatan, dan seluruh KPU kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo. Dalam pemaparannya, KPU Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa jumlah pemilih Semester II Tahun 2025 mencapai 906.319 pemilih, terdiri atas 450.925 laki-laki dan 455.394 perempuan. Jumlah ini meningkat 3% dibandingkan DPT Pilkada 2024 dan naik 2% dibandingkan DPB Semester I 2025. Dari 6 kabupaten/kota, tercatat 40.283 pemilih baru, sementara pemilih kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 18.405 dan perubahan data mencapai 23.727 pemilih. Data ini menunjukkan proses pemutakhiran berjalan aktif dan konsisten. KPU Bone Bolango hadir sebagai bentuk dukungan terhadap penyajian data pemilih yang akurat dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. #KPUMelayani ....

KPU Kabupaten Bone Bolango menggelar Bimbingan Teknis Penggunaan Tata Naskah Dinas, Penataan dan Penilaian Arsip, serta Penggunaan Aplikasi SRIKANDI
#TemanPemilih, KPU Kabupaten Bone Bolango menggelar Bimbingan Teknis Penggunaan Tata Naskah Dinas, Penataan dan Penilaian Arsip, serta Penggunaan Aplikasi SRIKANDI, Senin, 08 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan KPU Bone Bolango sebagai upaya memperkuat kualitas tata kelola administrasi dan kearsipan. Ketua KPU Bone Bolango Sutenty Lamuhu membuka kegiatan secara langsung. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa pembahasan mengenai tata kelola arsip bukan sekadar urusan administrasi, tetapi merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan organisasi. “Kearsipan adalah tata kelola mendasar. Kegiatan ini menjadi sangat penting bagi KPU yang bekerja berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, saya berharap seluruh jajaran sekretariat dapat mengikuti bimtek ini dengan sungguh-sungguh,” ujarnya. Beliau juga menekankan bahwa Bimtek ini diharapkan mampu menghasilkan output berupa peningkatan pemahaman peserta terkait penatausahaan dan penataan kearsipan. “Yang terpenting adalah bagaimana setelah kegiatan ini kita mampu membangun budaya tertib arsip. Ini adalah kerja-kerja bersama yang harus kita wujudkan. Bukan hanya menambah wawasan, tetapi bagaimana menerapkan materi yang disampaikan narasumber dalam pekerjaan sehari-hari,” tambahnya. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, Dinas Perpustakaan Kabupaten Bone Bolango, serta KPU Provinsi Gorontalo, yang memberikan materi terkait tata naskah dinas, standar kearsipan, hingga penggunaan aplikasi SRIKANDI. Bimtek turut dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Bone Bolango, Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo bersama jajaran, serta Sekretaris KPU Bone Bolango dan seluruh jajaran sekretariat. #KPUMelayani ....

Publikasi
Opini

Demokrasi tidak hanya diukur dari saat rakyat menggunakan hak pilihnya, tetapi juga dari seberapa akurat data yang menopang setiap prosesnya. Di balik setiap pemilu yang kredibel, terdapat kerja panjang dan berjenjang untuk memastikan setiap angka dan nama benar adanya. Bagi KPU, data bukan sekadar deretan informasi administratif, melainkan fondasi legitimasi. Karena data senantiasa bergerak seiring dinamika sosial, politik, dan demografi, akurasi menjadi nadi yang harus terus dijaga melalui verifikasi dan pemutakhiran yang berkelanjutan. Di tengah persiapan menuju tahapan pemilu, KPU memikul tanggung jawab ganda: memastikan updating data partai politik yang memenuhi standar demokrasi, sekaligus memperbarui data pemilih agar setiap warga terjamin hak konstitusionalnya. Dua pekerjaan besar ini mungkin tampak terpisah, namun sejatinya saling bertaut pada satu tujuan yang sama, yaitu menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Di situlah KPU meniti akurasi, menjaga validitas data, dan meneguhkan integritas demi memastikan denyut demokrasi tetap seirama dengan harapan dan aturan. Akurasi sebagai Basis Demokrasi yang Bergerak Setiap penyelenggaraan pemilu berpijak pada data yang akurat. Data menjadi fondasi dari seluruh keputusan, mulai dari penetapan peserta hingga daftar pemilih. Jika data keliru, maka legitimasi hasil pun dapat dipertanyakan bahkan digugat. Karena itu, akurasi menjadi penting bukan hanya sebagai kebutuhan teknis, tetapi juga sebagai prasyarat moral dalam menjaga keadilan dan kepercayaan publik. Di tangan penyelenggara pemilu, setiap nama dan angka memiliki konsekuensi demokratis: satu kesalahan kecil dapat memengaruhi hak konstitusional seorang warga negara maupun kredibilitas lembaga. Data tidak pernah statis, melainkan senantiasa bergerak mengikuti dinamika masyarakat: orang lahir dan meninggal, pindah domisili, berganti status pekerjaan, atau berubah afiliasi politik. Perubahan-perubahan ini menuntut sistem yang adaptif dan berkelanjutan. Menjaga akurasi berarti memahami bahwa demokrasi hidup dalam arus perubahan tersebut. Inilah sebabnya, pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU menjadi proses yang tak pernah selesai, karena yang dijaga bukan hanya data, melainkan denyut kehidupan demokrasi itu sendiri. Menjaga akurasi dalam konteks penyelenggaraan pemilu tidak hanya berbicara tentang ketepatan angka, tetapi juga tentang ketelitian dalam menafsirkan data sebagai potret nyata masyarakat. Di lapangan, data sering kali bersinggungan dengan realitas sosial yang kompleks: perbedaan administratif, perubahan kependudukan, hingga persoalan validitas dokumen. Karena itu, akurasi menuntut tidak hanya kecermatan teknis, tetapi juga kepekaan sosial dan integritas kelembagaan. Setiap nama yang tercatat merepresentasikan hak politik seseorang, sementara setiap data yang diperbarui mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin kesetaraan akses terhadap proses demokrasi. Hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ditegaskan dalam Pasal 198 dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menjaga akurasi berarti menjaga kepercayaan publik. Setiap angka dan nama yang tercatat memuat harapan agar proses demokrasi berlangsung jujur, terbuka, dan setara. Akurasi yang terjamin memperkuat legitimasi hasil, sekaligus memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Sebaliknya, ketidakakuratan data, sekecil apa pun, dapat menimbulkan keraguan dan mencederai keyakinan publik terhadap proses demokrasi. Karena itu, akurasi harus dipahami bukan semata urusan administrasi, tetapi juga amanat moral yang menegaskan peran lembaga penyelenggara dalam menjaga kemurnian suara rakyat. Pada akhirnya, akurasi tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan sistem, tetapi juga cermin dedikasi lembaga penyelenggara dalam melayani demokrasi. Akurasi merupakan bentuk pengabdian teknis sekaligus komitmen moral untuk memastikan bahwa pemilih dan peserta pemilu memperoleh pelayanan yang adil, setara, dan berbasis data yang benar. Di sinilah KPU meneguhkan perannya sebagai pelaksana teknis yang menjembatani pemilih dan partai politik sebagai dua sisi utama demokrasi melalui kerja berjenjang yang teliti, transparan, dan berintegritas. Dengan demikian, akurasi bukan sekadar instrumen administratif, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk memilih dan dipilih. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan: Menjaga Nama, Menjaga Suara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan pilar penting dalam menjaga kualitas dan legitimasi pemilu. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara. Berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU secara berjenjang memperbarui data agar daftar pemilih selalu mutakhir, akurat, dan komprehensif. Melalui mekanisme ini, KPU memastikan setiap warga yang memenuhi syarat terdaftar dengan benar, sehingga tidak ada suara rakyat yang hilang akibat ketidaktepatan data. Menjaga akurasi data berarti menjaga hak pilih warga negara. Karena itu, KPU bertanggung jawab memastikan seluruh proses pemutakhiran berjalan hati-hati, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 510, yang menegaskan larangan bagi siapa pun untuk menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Dengan demikian, setiap langkah pemutakhiran data yang dilakukan KPU merupakan upaya preventif agar hak warga tetap terjamin dan kepercayaan publik terhadap demokrasi terus terjaga. Pemutakhiran data pemilih juga mencakup proses pencatatan pemilih baru dan penetapan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS). Dinamika kependudukan membuat data pemilih terus berubah: warga yang baru genap berusia tujuh belas tahun, menikah, atau telah memenuhi syarat hukum lainnya perlu segera dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Sebaliknya, mereka yang telah meninggal dunia, berpindah domisili ke luar daerah pemilihan, berstatus pekerjaan sebagai anggota TNI/Polri atau kehilangan hak pilih karena alasan hukum harus dicoret dari daftar. Keseimbangan antara penambahan dan penghapusan data ini menjadi bagian penting dari prinsip akurasi, agar daftar pemilih tidak hanya lengkap tetapi juga sahih. Setiap perubahan nama dalam daftar bukan sekadar administrasi kependudukan, melainkan wujud tanggung jawab negara melalui KPU dalam memastikan bahwa hanya mereka yang berhak yang tercatat, dan tidak ada satu pun warga yang layak memilih terabaikan. Selain pemilih baru dan TMS, KPU juga memastikan pemutakhiran data mencakup kelompok pemilih penyandang disabilitas. Kelompok ini sering menghadapi hambatan fisik maupun sosial yang berpotensi menghalangi akses mereka terhadap hak pilih. Melalui mekanisme pendataan berjenjang dan koordinasi dengan instansi terkait, KPU memastikan data pemilih disabilitas tercatat secara akurat, baik jenis disabilitas maupun kebutuhan khusus mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Upaya ini menegaskan komitmen KPU untuk mewujudkan pemilu yang inklusif, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi apa pun. Dengan demikian, akurasi dalam konteks ini tidak hanya bermakna ketepatan data, tetapi juga keadilan bagi semua pemilih. Melalui pendataan yang inklusif dan akurat, KPU memastikan seluruh warga negara, tanpa kecuali, menjadi bagian dari denyut demokrasi yang hidup dan terus bergerak. Pada akhirnya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan mencerminkan bagaimana demokrasi bekerja melalui ketepatan dan kejujuran data. Data pemilih akan selalu bergerak, karena ia berkaitan dengan orang hidup yang terus mengalami perubahan: lahir, berpindah, menikah, atau meninggal. Dari pemilih baru hingga disabilitas, dari dinamika domisili hingga perbedaan generasi, seluruh proses ini menunjukkan bahwa akurasi bukan sekadar urusan teknis, tetapi bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk menjaga kehidupan demokrasi tetap berdetak. Melalui PDPB, KPU menegaskan komitmennya agar hak setiap warga negara tetap terdaftar dan terlayani dengan benar, sembari memastikan fondasi data yang akurat bagi tahapan pemilu berikutnya, termasuk verifikasi partai politik sebagai peserta. Pemutakhiran Data Partai Politik: Meneguhkan Integritas Peserta Pemilu Pemutakhiran data partai politik merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas peserta pemilu dan memastikan partai politik selalu berada dalam kondisi administratif yang tertib dan transparan. Berdasarkan Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, KPU mewajibkan partai politik melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Pemutakhiran ini meliputi pembaruan struktur kepengurusan, keanggotaan, dan domisili kantor, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen (zipper system) dalam susunan pengurus. Proses ini dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada semester pertama (Januari–Juni) dan semester kedua (Juli–Desember), sebagai bentuk konsistensi KPU dalam menjaga agar data partai politik tetap valid, mutakhir, dan akuntabel. Pemutakhiran data partai politik tidak hanya penting bagi tertib administrasi kelembagaan, tetapi juga menjadi sarana menjaga kemurnian partisipasi politik masyarakat. Melalui SIPOL, publik dapat memastikan bahwa data pribadi mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tanpa persetujuan. KPU mendorong partai politik agar aktif memperbarui data keanggotaan, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jika namanya tercatut sebagai anggota partai tanpa sepengetahuan. Langkah ini menjadi bagian dari transparansi dan perlindungan hak sipil warga negara, terutama bagi mereka yang berstatus sebagai aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, penyelenggara pemilu, maupun kelompok profesi lain yang secara hukum dilarang berafiliasi dengan partai politik. Dengan demikian, proses pemutakhiran bukan hanya memastikan partai politik tetap terdata dengan benar, tetapi juga meneguhkan kepercayaan publik bahwa data politik dikelola secara jujur dan bertanggung jawab. Pemutakhiran data partai politik juga memiliki makna strategis dalam menjaga kedisiplinan organisasi dan memperkuat tata kelola internal partai. Melalui pembaruan berkala, partai politik dituntut untuk memastikan struktur kepengurusan di setiap tingkatan berjalan aktif dan sesuai ketentuan hukum, termasuk pemenuhan zipper system dalam kepengurusan pusat hingga daerah. Proses ini mendorong partai untuk tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memperkuat prinsip kesetaraan dan regenerasi politik. Dengan data yang selalu diperbarui, keberadaan partai menjadi lebih akuntabel, terbuka terhadap publik, dan mampu menegaskan fungsinya sebagai sarana partisipasi politik yang sehat dan berintegritas. Bagi KPU, pemutakhiran data partai politik tidak hanya bertujuan memastikan kebenaran administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga integritas sistem kepartaian secara keseluruhan. Melalui SIPOL, proses pemutakhiran tidak lagi bergantung pada dokumen manual, melainkan berbasis data digital yang dapat ditelusuri dan diaudit. Setiap perubahan yang dilakukan partai terekam secara sistematis, sehingga meningkatkan akuntabilitas baik bagi partai politik maupun bagi KPU sebagai penyelenggara. Transparansi ini mempersempit ruang bagi penyimpangan dan memperkuat kepercayaan publik bahwa proses pendaftaran, verifikasi, dan pemutakhiran data partai berjalan sesuai prinsip keterbukaan, keadilan, dan profesionalitas. Pada akhirnya, pemutakhiran data partai politik menjadi bagian dari tanggung jawab bersama antara KPU dan peserta pemilu dalam membangun kejujuran politik. Melalui pembaruan data yang rutin dan berbasis sistem, partai politik tidak hanya menunjukkan kepatuhan administratif, tetapi juga komitmen moral untuk menjaga kredibilitas sebagai peserta demokrasi. Di sisi lain, KPU menegaskan perannya sebagai pelaksana teknis yang memastikan seluruh proses berjalan terbuka dan akuntabel. Ketika data partai politik terkelola dengan baik dan dapat dipercaya, maka kepercayaan publik terhadap sistem kepemiluan akan semakin kokoh, menjadi prasyarat penting bagi demokrasi yang berintegritas. Konvergensi Data dan Kepercayaan Publik: Menyiapkan Demokrasi yang Berintegritas Di luar masa tahapan pemilu, KPU tetap menjalankan kerja-kerja mendasar yang menjadi nadi dari penyelenggaraan demokrasi, yakni memastikan akurasi data pemilih dan data partai politik. Dua elemen ini merupakan fondasi utama yang menentukan legitimasi dan kelancaran seluruh proses pemilihan. Meski tahapan pemilu belum berjalan, aktivitas verifikasi, pembaruan, dan sinkronisasi data terus dilakukan secara berjenjang agar ketika tahapan resmi dimulai, seluruh data telah siap, valid, dan dapat digunakan tanpa menimbulkan keraguan. Komitmen ini menegaskan bahwa keberadaan KPU: demokrasi tidak hanya hidup di masa kampanye atau pemungutan suara, tetapi juga tumbuh dari ketekunan menjaga akurasi data di masa jeda, ketika publik mungkin tidak sedang menyorot kinerjanya. Keberadaan KPU tidak semata diukur dari aktivitas penyelenggaraan pemilu, tetapi dari kemampuannya menjaga ekosistem demokrasi tetap berdenyut di luar masa tahapan. Dalam keseharian yang senyap dari hiruk-pikuk politik, KPU tetap bekerja memastikan bahwa data pemilih dan data partai politik dikelola dengan akurat, aman, dan terlindungi. Tanggung jawab ini mencakup pula kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menegaskan pentingnya pengelolaan informasi secara hati-hati, terbatas, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, keberadaan KPU menjadi penyangga utama yang memastikan demokrasi tidak kehilangan fondasinya: kepercayaan publik terhadap data dan proses yang jujur. Demokrasi tidak berdiri sendiri, tapi memerlukan penjaga yang memastikan setiap tahapannya berlangsung jujur, terukur, dan berkesinambungan. Dalam konteks itu, KPU hadir bukan hanya sebagai pelaksana teknis pemilu, tetapi sebagai institusi yang memelihara denyut kehidupan demokrasi agar tetap berdetak antara satu pemilihan dan pemilihan berikutnya. Tanpa kerja berkelanjutan dalam menjaga akurasi data dan integritas sistem, demokrasi akan kehilangan ritme kepercayaannya. Karena itu, keberadaan KPU menjadi penanda bahwa demokrasi tidak berhenti pada hasil pemungutan suara, melainkan terus hidup melalui kerja sunyi menjaga keabsahan data, kebenaran proses, dan kepercayaan rakyat. Pada akhirnya, menjaga akurasi data bukan hanya pekerjaan administratif, tetapi bagian dari menjaga kepercayaan publik terhadap sistem politik itu sendiri. Di dalam setiap nama pemilih dan setiap anggota partai yang terdaftar, tersimpan legitimasi negara dan masa depan demokrasi. KPU, dengan seluruh kerja teknis dan moralnya, menjadi ruang tempat kejujuran dan akurasi bertemu, tempat demokrasi menemukan bentuk nyatanya. Ketika data dijaga, kepercayaan dipelihara, dan integritas ditegakkan, maka demokrasi akan terus berdenyut meski pemilihan telah usai dan hiruk-pikuk politik mereda. Dalam kerja yang senyap itulah, KPU meneguhkan eksistensinya sebagai penjaga nadi demokrasi, memastikan bahwa kedaulatan rakyat tetap hidup, akurat, dan terhormat. Penulis : Shaqti Qhalbudien Yusuf (Anggota KPU Kab. Bone Bolango)

Dalam penyelenggaraan demokrasi, keterlibatan perempuan selalu menjadi perhatian penting. Perempuan sebagai kelompok masyarakat yang jumlahnya sekitar 50,3% sedikit lebih banyak dibanding laki-laki, memiliki hak yang sama untuk berperan sebagai pemilih, kandidat, maupun penyelenggara pemilu. Kita memahami betul bahwa tanpa keterlibatan penuh perempuan, kualitas demokrasi bangsa ini akan selalu timpang, karena separuh suara rakyat tak boleh hanya diperlakukan sebagai pelengkap. Penerapan mekanisme zipper system dalam pencalonan legislatif, merupakan salah satu upaya untuk memastikan keterwakilan mereka dalam kontestasi politik. Tujuannya jelas: memastikan perempuan tidak hanya hadir, tetapi juga memiliki peluang strategis untuk dipilih. Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kuota formal saja tidak cukup. Kita sering menyaksikan bagaimana kehadiran perempuan berhenti pada angka, sementara kapasitas, kompetensi, dan kontribusi strategis mereka belum sepenuhnya diberdayakan. Padahal, di satu sisi, banyak perempuan memiliki kemampuan luar biasa dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan proses politik. Di sisi lain, akses, budaya, dan stigma sosial masih menjadi penghalang nyata bagi partisipasi penuh mereka. Kuota hadir sebagai pemicu, tetapi keterlibatan substantif membutuhkan pendidikan, persiapan, dan pengakuan nyata atas kapasitas yang mereka miliki. Tulisan ini menelusuri perjalanan perempuan dalam demokrasi, menyoroti tantangan dan peluang mereka sebagai pemilih, kandidat, dan penyelenggara pemilu. Kita ingin melihat lebih jauh bahwa memberdayakan perempuan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi bangsa secara keseluruhan. Kuota vs Kesiapan: Paradoks Zipper System Realitas demokrasi kita menunjukkan, kehadiran perempuan seringkali dipastikan lewat instrumen formal, salah satunya zipper system. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan diperinci dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023, yang mewajibkan partai politik menempatkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif dengan pola penyusunan bergantian. Secara normatif, aturan ini tampak sebagai langkah progresif yang menjanjikan kesetaraan. Namun, praktik di lapangan sering kali berkata lain. Kuota yang dimaksudkan untuk membuka akses politik justru berakhir menjadi formalitas angka semata. Kita kerap menyaksikan perempuan masuk daftar calon bukan karena kesiapan atau kapasitas, melainkan sekadar untuk memenuhi syarat hukum. Dalam kondisi seperti ini, meritokrasi terkikis, digantikan simbolisme yang mereduksi kualitas demokrasi. Paradoks ini makin mencolok jika kita melihat fakta demografi: jumlah perempuan di Indonesia sedikit lebih banyak daripada laki-laki. Secara logis, ketersediaan kader perempuan seharusnya tidak menjadi masalah. Namun kenyataan menunjukkan sebaliknya, bahwa “stok” kader yang benar-benar siap tampil tetap langka. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah persoalannya ada pada kapasitas perempuan yang belum optimal, atau pada akses politik yang masih tertutup rapat oleh struktur patriarki? Seharusnya, batas minimal dalam zipper system menjadi pemicu, bukan pengganti persiapan nyata. Tanpa penguatan kapasitas, kuota hanya melahirkan ilusi representasi: perempuan memang hadir secara formal, tetapi kualitas kepemimpinan mereka tidak terjamin. Politik pun berubah menjadi panggung simbolik, bukan arena meritokrasi. Refleksi ini menuntut keseriusan kita bersama: jika demokrasi ingin benar-benar inklusif, keterwakilan perempuan tidak cukup diukur dari kuota semata. Yang dibutuhkan adalah kesiapan, kapasitas, dan keberanian untuk berkontribusi secara nyata. Zipper system hanyalah alat; tanpa pemberdayaan substantif, ia akan tetap menjadi angka kosong yang terlihat di permukaan, kehilangan makna dalam praktik. Budaya Patriarki dan Stigma Sosial Jika kuota membuka pintu formal, budaya patriarki dan stigma sosial sering kali menjadi kunci yang menutupinya kembali. Kita masih hidup dalam warisan budaya yang membatasi peran perempuan pada ruang domestik, seolah-olah ruang publik bukanlah milik mereka. Norma yang tampak wajar ini, tanpa kita sadari, menimbulkan keraguan, pesimisme, dan rasa takut bagi banyak perempuan untuk tampil di panggung politik. Ironisnya, ketika kesempatan benar-benar diberikan, perempuan berulang kali membuktikan kapasitasnya. Sejarah menjadi saksi: Nusaibah binti Ka’ab (Ummu Imarah) tampil gagah dalam Perang Uhud, melindungi Rasulullah SAW dengan keberanian luar biasa. Rufaidah al-Aslamiyah membangun sistem medis pertama di Madinah dengan dedikasi yang menyelamatkan banyak nyawa. Di tanah air, sosok seperti Cut Nyak Dien, R.A. Kartini, dan Dewi Sartika menunjukkan bahwa perempuan bukan sekadar pelengkap, melainkan penggerak sejarah bangsa. Namun, di panggung politik modern, stigma sosial masih kerap mengerdilkan peran perempuan. Mereka diharapkan hadir, tetapi dengan syarat: jangan terlalu vokal, jangan terlalu dominan, jangan mengganggu “tatanan”. Akibatnya, banyak perempuan ditempatkan hanya untuk memenuhi angka, bukan sebagai peserta yang disiapkan dengan serius. Kuota yang semula dimaksudkan sebagai pemicu representasi, ketika bersinggungan dengan budaya patriarki, justru berisiko berubah menjadi simbol kosong tanpa substansi. Kita perlu jujur mengakui paradoks ini: kemampuan perempuan sudah terbukti sepanjang sejarah, tetapi budaya modern masih mengulang pola lama yang mengekang. Demokrasi yang sehat tidak cukup hanya memberi ruang formal; ia harus membongkar belenggu budaya yang menghalangi perempuan untuk benar-benar berdaya. Transisi ini membawa kita pada pertanyaan berikutnya: jika perempuan sudah berkali-kali membuktikan diri, lalu bagaimana mereka bisa berperan nyata dalam politik dan ruang publik hari ini?. Dari belenggu budaya patriarki, kita belajar satu hal penting: keterbatasan akses bukanlah cerminan keterbatasan kemampuan perempuan. Saat ruang benar-benar terbuka, terlihat jelas bagaimana perempuan mampu mengambil peran nyata dalam politik maupun ruang publik. Kapasitas Perempuan dalam Politik dan Ruang Publik Di panggung demokrasi modern, banyak perempuan hadir bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai penggerak perubahan. Kita bisa menyaksikan perempuan memimpin lembaga penyelenggara pemilu di berbagai daerah, mengelola proses yang rumit dengan ketegasan dan integritas. Kita juga melihat perempuan yang berani maju sebagai kandidat legislatif, kepala daerah, atau pemimpin partai politik, memperjuangkan aspirasi yang sering kali diabaikan oleh sistem politik yang didominasi laki-laki. Kapasitas mereka bukan sekadar formalitas kuota. Cara berpikir relasional, empati, dan naluri keibuan yang khas menghadirkan perspektif berbeda dalam pengambilan keputusan politik. Dalam banyak kasus, hal ini menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, berpihak pada kelompok rentan, serta memperkuat keadilan sosial. Kita bisa melihatnya pada kebijakan-kebijakan yang menekankan perlindungan anak, kesejahteraan keluarga, kesehatan masyarakat, dan pendidikan, merupakan isu-isu yang sering kali diperjuangkan dengan lebih serius oleh legislator perempuan. Namun, paradoks tetap mengintai. Zipper system yang semula dimaksudkan sebagai pintu masuk sering diterjemahkan sebatas angka, bukan sebagai ruang untuk menumbuhkan kapasitas kepemimpinan. Kita sering menyaksikan perempuan didorong maju tanpa persiapan memadai, sehingga meritokrasi tersisih oleh simbolisme. Padahal, perempuan yang benar-benar disiapkan mampu menyeimbangkan kepemimpinan, memperkuat kualitas keputusan politik, dan menghadirkan legitimasi demokrasi yang lebih kokoh. Sejarah dan fakta modern sama-sama memberi kita pelajaran: ketika perempuan diberi ruang, kesempatan, dan pengakuan, mereka bukan sekadar ikut serta, melainkan hadir sebagai kekuatan strategis yang menentukan arah. Kepemimpinan, visi politik, dan integritas sejatinya tidak pernah soal gender, melainkan soal kapasitas dan kesiapan. Dari sini kita sampai pada kenyataan berikutnya: perempuan tidak hanya hadir sebagai pemimpin atau kandidat, tetapi juga sebagai pemilih aktif yang memegang pengaruh strategis dalam menentukan kualitas demokrasi. Perempuan sebagai Pemilih dan Penggerak Demokrasi Partisipasi perempuan dalam demokrasi tidak berhenti pada keterwakilan di daftar calon. Lebih dari itu, mereka adalah pemilih aktif yang menentukan arah politik bangsa. Jumlah perempuan yang sedikit lebih besar dibanding laki-laki justru kontras dengan realitas politik: suara mereka sering diperlakukan sebagai tambahan belaka, padahal sejatinya menjadi penentu legitimasi kepemimpinan dan kualitas demokrasi. Kita tahu bahwa perempuan tidak hadir sebagai massa pasif. Mereka adalah pembentuk opini, penggerak komunitas, dan penentu hasil pemilu. Dalam banyak peristiwa, suara perempuan menjadi penentu kemenangan kandidat, bahkan mengubah peta politik. Sayangnya, peran besar ini masih sering dipandang sebelah mata. Perempuan dianggap hanya sebagai angka dalam statistik pemilih, padahal kontribusi mereka jauh lebih substansial. Ketika perempuan diberdayakan untuk menggunakan hak pilihnya secara kritis, arah kebijakan publik pun ikut berubah. Kita bisa melihat bagaimana perempuan yang sadar akan hak politiknya cenderung mendorong isu-isu yang lebih inklusif: pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan kesejahteraan keluarga. Isu-isu yang sering dipinggirkan dalam wacana politik maskulin justru mendapat ruang ketika suara perempuan diperhitungkan dengan serius. Namun, tantangan besar tetap ada. Budaya patriarki dan stigma sosial masih membuat banyak perempuan ragu untuk bersuara kritis atau terlibat aktif dalam proses politik. Kita sering menjumpai bagaimana perempuan yang berani menyampaikan pandangan dianggap “kurang pantas,” sementara yang diam dianggap sesuai dengan norma. Paradoks ini membuat partisipasi perempuan seolah dibatasi oleh aturan tak tertulis yang membungkam potensi mereka. Refleksi ini membawa kita pada pemahaman penting: perempuan sebagai pemilih bukanlah sekadar elemen statistik. Mereka adalah kekuatan pengubah arah demokrasi, penentu kualitas kepemimpinan, dan penyeimbang dalam keputusan politik. Jika suara perempuan dihitung, didengar, dan diterjemahkan ke dalam kebijakan, maka demokrasi menjadi lebih adil, lebih bermakna, dan lebih inklusif. Transisi ini mengantarkan kita pada dimensi berikutnya: perempuan tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai kandidat dan penyelenggara, posisi di mana mereka ikut menentukan jalannya demokrasi dari dalam. Perempuan sebagai Kandidat dan Penyelenggara Dari bilik suara, perjalanan perempuan dalam demokrasi berlanjut ke panggung yang lebih menantang: pencalonan politik dan penyelenggaraan pemilu. Jika sebagai pemilih perempuan memegang kendali legitimasi, maka sebagai kandidat dan penyelenggara mereka adalah arsitek yang membentuk wajah demokrasi itu sendiri. Sebagai kandidat, perempuan membawa nuansa baru dalam politik. Mereka menghadirkan perspektif yang lebih inklusif, keberpihakan pada kelompok rentan, serta kepekaan sosial yang lahir dari pengalaman hidup sehari-hari. Kita dapat melihat bahwa ketika perempuan menduduki kursi legislatif atau jabatan publik, kebijakan yang lahir lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Dengan kata lain, kehadiran mereka memperluas cakrawala politik yang kerap sempit terjebak pada perebutan kekuasaan semata. Namun, jalan menuju kursi politik tidak pernah mudah. Perempuan sering menghadapi hambatan ganda: sistem politik yang belum ramah gender, serta stigma sosial yang terus melekat. Mereka dipertanyakan bukan pada gagasan atau program, melainkan pada status keluarga, peran domestik, bahkan penampilan fisik. Politik menjadi arena yang lebih berat, karena selain berkompetisi dengan lawan politik, mereka juga harus melawan stereotip dan prasangka yang mengakar. Sebagai penyelenggara pemilu, perempuan memegang peran strategis yang tak kalah penting. Mereka adalah penjaga integritas proses demokrasi, memastikan setiap tahapan berjalan jujur, transparan, dan adil. Kehadiran mereka bukan hanya menambah keragaman perspektif, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Kita sering melihat bagaimana penyelenggara perempuan menunjukkan ketelitian, ketegasan, dan ketahanan menghadapi tekanan politik, serta kepekaan terhadap potensi diskriminasi. Sayangnya, di banyak tempat, kehadiran perempuan dalam posisi ini masih direduksi menjadi sekadar pemenuhan kuota. Bukan sedikit perempuan yang ditempatkan distruktur penyelenggara atau daftar kandidat hanya untuk memenuhi aturan formal, tanpa benar-benar diberdayakan. Padahal meritokrasi menuntut sebaliknya: perempuan yang kompeten, berintegritas, dan visioner harus diberi ruang untuk memimpin, bukan sekadar menghiasi struktur. Paradoksnya jelas: perempuan dituntut hadir, tetapi tidak selalu diberi ruang untuk berdaya. Demokrasi yang berhenti pada angka tidak akan pernah melahirkan kualitas. Hanya ketika perempuan dipersiapkan, didukung, dan diakui kapasitasnya, mereka dapat menjadi pilar yang memperkuat legitimasi, profesionalisme, dan integritas demokrasi. Dari pemilih hingga penyelenggara, perjalanan perempuan dalam demokrasi menyingkap satu pesan penting: keterwakilan formal hanyalah permulaan. Yang menentukan adalah kesediaan demokrasi untuk menerima keterlibatan substantif mereka, yaitu sebagai penggerak perubahan, penyeimbang kepemimpinan, dan penjaga kualitas bangsa. Inklusivitas dan Keadilan dalam Demokrasi Perjalanan panjang membicarakan perempuan sebagai pemilih, kandidat, dan penyelenggara membawa kita pada satu kesadaran: demokrasi yang sehat tidak cukup hanya dihitung dari kuota. Kehadiran perempuan dalam politik bukanlah soal angka, melainkan soal kualitas keterlibatan, kesiapan, dan kapasitas nyata yang mereka hadirkan. Kuota 30% dalam zipper system memang langkah progresif, tetapi jika berhenti menjadi formalitas, ia hanya berubah menjadi simbol kosong. Demokrasi yang bergantung pada angka semata akan kehilangan substansinya, karena meritokrasi tergeser oleh simbolisme. Kuota seharusnya menjadi pemicu, bukan pengganti; jembatan menuju keterlibatan sejati, bukan sekadar tanda di atas kertas. Lebih dari itu, kita diingatkan bahwa budaya patriarki dan stigma sosial adalah penghalang terbesar yang masih menahan perempuan. Demokrasi yang hanya membuka ruang di regulasi, tetapi menutup pintu di lapangan, sejatinya adalah demokrasi pincang. Kita tidak bisa terus membiarkan perempuan dilihat sebagai pelengkap; mereka adalah penentu arah kebijakan, penjaga integritas pemilu, dan penggerak legitimasi politik. Sejarah dan fakta modern sama-sama telah berbicara lantang: ketika perempuan diberi ruang, mereka membuktikan kapasitas strategisnya. Mereka menghadirkan perspektif inklusif, memperjuangkan kepentingan publik yang lebih luas, dan menyeimbangkan kepemimpinan yang sering terjebak dalam perebutan kekuasaan. Karena itu, memberdayakan perempuan bukan sekadar kewajiban moral, melainkan investasi kualitas bagi masa depan bangsa. Demokrasi yang egaliter hanya mungkin terwujud jika perempuan diperlakukan sebagai subjek yang berdaya, disiapkan dengan serius, dan dihargai kapasitasnya. Demokrasi yang menutup pintu bagi perempuan bukanlah demokrasi yang sehat. Demokrasi yang memperkecil suara mereka bukanlah demokrasi yang bermartabat. Maka, jika kita sungguh-sungguh ingin membangun demokrasi yang kuat, legitimate, dan adil, tidak ada jalan lain kecuali memastikan perempuan hadir bukan sebagai angka, melainkan sebagai kekuatan yang hidup, menggerakkan, dan menentukan arah masa depan politik Indonesia. Penulis : Shaqti Qhalbudien Yusuf (Anggota KPU Kab. Bone Bolango)

Politik, Amanah, dan Citra yang Ternodai Banyak orang Indonesia menjadi sinis setiap kali mendengar kata “politik”, sebagiannya muak, dan sebagian lain memilih apatis. Sebab, politik kerap kali diasosiasikan sebagai dunia yang penuh tipu daya, sarat kepentingan pribadi, dan kotor, di dalamnya dipenuhi dengan perebutan kursi, janji kosong, atau praktik uang yang seringkali mencederai esensi demokrasi. Namun sejatinya, politik adalah amanah yang dititipkan oleh Tuhan melalui rakyat, yang bila dijalankan dengan benar, bisa menjadi ibadah sosial. Tetapi mari kita jujur: apakah politik selalu kotor, atau manusialah yang mengotorinya? Politik pada hakikatnya adalah seni mengelola kehidupan bersama, dan di situlah letak amanahnya. Amanah berarti titipan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Bila amanah ini diselewengkan, politik menjadi alat penindasan. Namun bila dijalankan dengan integritas, politik berubah menjadi ibadah sosial yang menjadi ladang pengabdian nyata untuk kesejahteraan rakyat dan menjaga keadilan. Politik sebagai Amanah dalam Perspektif Sejarah. Gagasan politik sebagai amanah bukanlah hal baru. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW menegaskan: “Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran.” (HR. Bukhari) Hadis ini memberi peringatan bahwa kekuasaan bukanlah hadiah, melainkan amanah. Jika jatuh ke tangan yang salah, kehancuranlah yang menanti. Abu Bakar Ash-Shiddiq, khalifah pertama, menegaskan hal ini ketika diangkat sebagai pemimpin: “Aku telah diangkat sebagai pemimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku benar, bantulah aku; jika aku salah, luruskanlah aku...” Pidato itu menunjukkan bahwa kekuasaan adalah beban moral, bukan kehormatan pribadi. Di Indonesia, Bung Hatta memberi teladan serupa. Ia menolak gaji berlebih sebagai pejabat negara karena sadar rakyat masih hidup dalam kemiskinan. Kekuasaan bagi Hatta adalah jalan pengabdian, bukan kesempatan memperkaya diri. Dari sini kita bisa mengambil i’tibar, bahwa sejarah selalu memberi pelajaran, bahwa politik akan bermartabat bila benar-benar dijalankan sebagai amanah. Realitas: Politik Uang vs Politik Bersih Sayangnya, praktik politik di lapangan sering jauh dari nilai amanah. Politik uang masih menjadi luka terbesar demokrasi kita. Menurut survei Indikator Politik Indonesia (2024), sekitar 40% pemilih mengaku pernah menerima tawaran uang atau barang dari kandidat saat pemilu. Sebagian warga bahkan menganggapnya hal biasa. Namun mari kita renungkan: apakah masa depan bangsa layak digadaikan hanya dengan Rp 50 ribu, sekantong sembako, jilbab atau bahkan selembar sarung?Padahal, suara yang kita jual hari ini akan menentukan arah kebijakan lima tahun ke depan. Beruntung, ada pula contoh politik bersih. Beberapa kepala daerah dan calon legislatif berhasil terpilih karena rekam jejak dan program, bukan karena membeli suara. Walau jumlahnya masih minoritas. Kisah ini memberi harapan, bahwa politik yang bermartabat bisa berpeluang menang, asal masyarakat sebagai pemilih sadar bahwa suara adalah amanah, bukan hanya sekedar barang dagangan. Data Partisipasi Pemilu: Cermin Kesadaran Kolektif Untuk memahami sejauh mana masyarakat memaknai amanah politik, mari kita lihat data partisipasi pemilu. Tahun Pemilu Partisipasi Pemilih 2004 78,2% 2009 72,6% 2014 69,6% 2019 81,97% 2024 81-82,4 (Sumber KPU, Litbang, Kompas, Wikipedia) Data ini menunjukkan tren menarik: setelah menurun di 2014, partisipasi kembali melonjak pada 2019 dan tetap tinggi di 2024. Menurut KPU RI, Pemilu 2024 mencatat 81,78% partisipasi untuk Pilpres dan angka serupa untuk Pileg DPR maupun DPD. Dari 204 juta pemilih terdaftar, sekitar 168 juta benar-benar hadir ke bilik suara. Artinya, masyarakat Indonesia tidak apatis. Sebagian besar masih percaya bahwa suara mereka penting. Pertanyaannya: apakah partisipasi ini sudah benar-benar mencerminkan kesadaran akan amanah? Pilkada Serentak 2024: Mengukur Kesadaran Lokal Jika kita menengok Pilkada Serentak 2024, gambarnya sedikit berbeda. Menurut data KPU RI: • Partisipasi pemilih rata-rata nasional: 71% • Pemilihan gubernur: 71,39% • Pemilihan bupati: 74,41% • Pemilihan wali kota: 67,74% (Sumber: KPU RI, Antara, Times Indonesia) Angka ini lebih rendah dari pemilu nasional. Apakah masyarakat lebih peduli dengan politik nasional ketimbang lokal? Atau apakah pendidikan politik di daerah belum cukup kuat?. Apapun jawabannya, data ini menjadi pengingat bahwa amanah politik harus dijaga, tidak hanya di level pusat, tetapi juga dari tingkatan grassroot yaitu dari desa, kecamatan, kabupaten/kota. Justru di tingkat lokal, kebijakan paling dekat dengan kehidupan sehari-hari rakyat. Refleksi: Suara sebagai Doa Setiap kali masuk ke bilik suara, saya merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar mencoblos kertas (surat suara). Di ruang yang ditutupi bilik kecil itu, tidak ada saksi, tidak ada tekanan, hanya saya, kertas, dan alat coblos yang beralaskan bantalan. Saat itulah saya sadar bahwa sejatinya, suara adalah doa yang akan menentukan nasib bangsa dalam lima tahun ke depan. Saya sering bertanya dalam hati: “Apakah pilihan saya ini akan membawa kebaikan bagi orang banyak? Ataukah justru menjadi luka yang diwariskan kepada generasi mendatang?” Refleksi ini membuat saya semakin yakin bahwa politik bukan hanya urusan elite, melainkan juga urusan hati nurani setiap warga negara. Jika suara kita niatkan sebagai doa, maka politik menjadi ibadah. Menghidupkan Amanah di Era Demokrasi Bagaimana agar politik sungguh menjadi ibadah sosial? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan bersama: Cerdas dalam Memilih, Kenali rekam jejak dan program kandidat. Jangan tergoda popularitas atau janji manis. Menolak Politik Uang dan Hoaks, Menolak amplop adalah cara sederhana tetapi revolusioner untuk menjaga martabat demokrasi. Aktif dalam Non-Tahapan, Demokrasi tidak berhenti setelah pencoblosan. Diskusi publik, literasi politik, dan pengawasan harus terus berjalan. Mengawasi Pemimpin, Warga bukan hanya pemilih, tetapi juga pengawas. Amanah tidak boleh dibiarkan tanpa kontrol. Menggunakan Ruang Digital dengan Bijak, Media sosial bisa menjadi ladang edukasi atau racun demokrasi. Bijaklah dalam menyebarkan informasi. Kesimpulan: Politik sebagai Jalan Pengabdian Politik bukanlah sekadar perebutan kursi. Ia adalah amanah yang melekat pada setiap orang entah itu pemimpin maupun warga negara. Setiap suara adalah titipan, setiap kebijakan adalah pertanggungjawaban. Sejarah Nabi, para khalifah, dan tokoh bangsa menunjukkan bahwa kekuasaan adalah beban moral, bukan privilege. Data partisipasi pemilu menegaskan bahwa rakyat Indonesia masih percaya pada demokrasi, meski tantangan politik uang dan rendahnya partisipasi lokal masih senantiasa membayangi.Akhirnya, politik akan menemukan kembali makna sucinya bila kita meniatkannya sebagai ibadah. Dengan begitu, demokrasi bukan hanya prosedur lima tahunan, melainkan jalan pengabdian yang luhur. “Setiap suara adalah doa, setiap keputusan adalah amanah. Dan sejatinya, demokrasi menjadi ibadah ketika dijalankan dengan penuh kesadaran.” Penulis : Shaqti Qhalbudien Yusuf (Anggota KPU Kab. Bone Bolango)

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Indonesia Ketika kita berbicara tentang perselisihan dalam pemilihan umum di Indonesia, tidak bisa lepas dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pemilihan umum, atau yang biasa disebut Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, merupakan proses untuk memilih para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Norma ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa perselisihan hasil Pemilu hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilu yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas Pemilu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting untuk menjamin keadilan dan kebenaran dalam proses demokrasi di Indonesia. Perselisihan hasil Pemilu harus diselesaikan dengan cara yang transparan, adil, dan akuntabel. Oleh karena itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk menjaga integritas dan stabilitas negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia. Apabila membandingkan konsepsi perumusan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman UUD 1945, kewenangan Mahkamah Agung dirumuskan secara non-limitatif, karena sebagian kewenangannya masih dapat ditentukan lebih lanjut dengan Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang memiliki kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, untuk menambah, melengkapi dan mereformulasikan ketentuan kewenangan Mahkamah Agung, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berbeda halnya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dirumuskan secara tegas dan limitatif, sehingga pembentuk Undang-Undang tidak berwenang menambah, dan secara a contrario juga tidak berwenang mengurangi kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang yang dibentuk. Oleh karena itu, apa pun yang menjadi dasar pijakan penentuan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan berwenang atau tidaknya terhadap suatu pengujian perkara, haruslah didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar dan bukan pada Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tunggal penafsir konstitusi di Indonesia. Namun, seiring berjalannya praktek ketatanegaraan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya melalui putusan nomor 72-73/PUU-II/2004. Putusan ini memperkuat konstitusionalitas bahwa pembentuk undang-undang dapat memastikan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) merupakan perluasan dari pengertian Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Meskipun Pilkada dan Pemilu dipisahkan secara tegas dalam undang-undang, namun penyelenggaraan Pilkada selalu berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013 juga menegaskan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pilkada. Putusan tersebut memastikan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pilkada akan terus berlaku selama belum ada undang-undang yang mengaturnya, demi menjaga integritas Pemilu dan Pilkada serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia Badan Peradilan Khusus Pilkada Pasca diterbitkannya UU Nomor 10 Tahun 2016 Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan keberwenangannya dalam memutus perselisihan tentang hasil Pilkada, kemudian diakomodir dalam beberapa Undang-Undang terkait, diantaranya: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”; dan/atau b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan kewenangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Namun, posisi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara limitiatif diberikan oleh UUD 1945 dinilai mencederai konstitusi itu sendiri. Perbedaan perumusan pemberian kewenangan kepada Mahkamah Agung yang jelas mengakomodir bahwa Mahkamah Agung “…mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”, tidak bisa dimaknai sama keberlakuannya terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara tegas dibatasi oleh UUD 1945. Prof. Enny Nurbaningsih sebagai salah satu pakar ketatanegaraan Indonesia juga menyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bahwa kewenangan dalam memutus perselisihan tentang hasil Pilkada yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, berpotensi menyebabkan Mahkamah Konstitusi kebanjiran perkara penyelesaian hasil Pilkada. Kondisi ini menyebabkan Mahkamah Konstitusi terpaksa berbagi fokus antara wewenang yang diberikan oleh UUD 1945, terutama pengujian Undang-Undang, dengan ketatnya batas waktu penyelesaian sengketa Pilkada yang diatur dalam Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Lebih lanjut, kepastian hukum yang seharusnya diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada, ternyata tidak dapat dimaknai kewenangannya akan berlaku secara terus menerus. Kewenangan ini dibatasi hingga Badan Peradilan Khusus Pilkada dibentuk. Namun, dalam pengaturan yang sama, Badan ini wajib dibentuk sebelum pelaksanaan Pilkada serentak nasional pada tahun 2024. Sayangnya, apabila berkaca dari negara-negara yang terlebih dahulu memiliki Badan Peradilan Khusus Pilkada, kompleksitas pembentukannya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan koordinasi yang matang antara lembaga negara dan seluruh pihak terkait untuk memastikan pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada dapat berjalan efektif dan efisien demi terciptanya kepastian hukum dalam perselisihan hasil Pilkada. Dikutip dari laman resmi Superior Electoral Court, Pengadilan Pilkada Brazil yang dibentuk pada tahun 1932 mengalami berbagai dinamika penyesuaian, baik dari sisi hukum maupun dinamika politik selama hampir 13 tahun. Selain itu, Tribunal de lo Contencioso Electoral sebagai pengadilan Pilkada di Mexico juga mengalami perjalanan panjang dari tahun 1987 dan baru menemui kestabilan penyelenggaraan penyelesaian perkara Pilkada setelah 20 tahun kemudian. Studi kasus dari 2 (dua) negara ini cukup menjelaskan bagaimana kompleksitas pembentukan suatu Badan Peradilan Khusus yang berwenang menyelesaikan perselisihan Pilkada di negaranya. Kompleksitas ini wajib dimitigasi oleh Indonesia untuk menjamin penyelenggaraan negara yang memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Terlebih, pelaksanaan Pemilu di tahun 2024 tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan Pilkada semata, namun juga mencakup Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945. Kondisi ini akan menyebabkan Mahkamah Konstitusi akan menghadapi ratusan bahkan ribuan perkara di tahun tersebut. Dalam konteks penyelenggaraan penyelesaian hasil Pilkada yang dapat mengakibatkan keraguan dan ketidakpuasan dari masyarakat, penulis berpendapat bahwa tindakan pencegahan yang paling efektif adalah dengan membentuk Badan Peradilan Khusus Pilkada yang memiliki kewenangan yang sama dengan Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai alternatif, lembaga negara yang sudah ada di bidang kepemiluan dapat diubah menjadi badan peradilan khusus Pilkada dengan memperhatikan keadilan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Namun, perlu diingat bahwa pembentukan badan peradilan khusus Pilkada bukanlah suatu hal yang mudah. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman negara lain yang mengalami kesulitan dalam membentuk badan peradilan khusus Pilkada. Oleh karena itu, upaya untuk membentuk badan peradilan khusus Pilkada perlu dipersiapkan secara matang agar dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan Pilkada di masa depan dapat berjalan dengan lebih adil dan transparan. Penulis : Shaqti Qhalbudien Yusuf (Anggota KPU Kab. Bone Bolango)

Politik media adalah sebuah bidang dalam politik yang memfokuskan pada peran dan dampak media dalam berbagai aspek politik. Istilah ini menggambarkan bagaimana media mengatasi, menyampaikan, dan memahami berita dan informasi politik. Politik media bukan hanya terbatas pada praktik-praktik media dalam menyebarkan informasi politik untuk memengaruhi pemilih dan proses politik, namun juga meliputi bagaimana media mempengaruhi opini publik melalui penyampaian berita dan penyampaian nilai politik melalui media. Politik media melibatkan berbagai aspek media, seperti distribusi berita, konten, teknologi, dan kepemilikan media. Ini juga mencakup berbagai topik, seperti media yang berperan dalam proses pemilihan, media yang berperan dalam proses politik, dan media yang memengaruhi konten politik. Politik media juga memperhitungkan bagaimana media dipengaruhi oleh kekuasaan politik dan bagaimana kekuasaan politik mempengaruhi media. Di Indonesia sendiri, media politik telah berkembang menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi proses politik. Berbagai jenis media, seperti media televisi, media sosial, media cetak, dan media online, memainkan peran yang berbeda dalam mempengaruhi opini publik dan proses politik. Media televisi, seperti program berita dan talkshow politik, memberikan informasi dan analisis politik yang sangat berpengaruh pada opini publik. Media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, memberikan cara bagi masyarakat untuk berbagi informasi dan berinteraksi dengan orang lain, membuatnya menjadi alat yang sangat efektif dalam mempengaruhi opini publik. Media cetak, seperti surat kabar nasional dan lokal, majalah, dan publikasi lainnya, masih memiliki pengaruh yang besar di Indonesia dan memainkan peran penting dalam mempengaruhi opini publik. Media online, seperti situs berita online, membuat informasi politik mudah diakses dan memberikan platform bagi masyarakat untuk berbagi informasi dan berinteraksi satu sama lain. Dalam keseluruhan, media politik di Indonesia memainkan peran penting dalam mempengaruhi opini publik dan proses politik, dan membutuhkan pengawasan yang baik untuk memastikan bahwa media bekerja secara adil dan objektif dalam mempengaruhi opini publik. Media merupakan aktor kunci dalam dunia politik Indonesia. Berkat media, masyarakat dapat terinformasi tentang isu-isu politik terbaru dan membentuk pandangan mereka sendiri. Media membantu mempromosikan transparansi dan keseimbangan dalam proses politik, memberikan peluang kepada semua pihak untuk berbicara, dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan netral. Namun, masih banyak orang yang merasa bahwa media tidak selalu memberikan representasi yang adil dari seluruh pandangan politik. Dalam demokrasi, media memegang peran sangat penting dalam membentuk opini publik dan membantu membuat keputusan politik yang informatif. Idealisme dan Keberpihakan Media Idealisme media adalah pandangan yang berpikir bahwa media memiliki tanggung jawab untuk memacu perubahan sosial yang positif. Ini menekankan bahwa media dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan nilai-nilai seperti keadilan, cinta, dan toleransi, dan membantu masyarakat untuk memahami nilai-nilai moral. Idealisme media percaya bahwa isi media harus berkonsentrasi pada memberikan kekuatan dan pemahaman nilai-nilai positif, bukan hanya untuk memperkaya nilai ekonomi atau hanya sekedar untuk hiburan. Dalam perannya sebagai sumber informasi publik, media kadang-kadang bertindak tidak adil. Ketidaksetaraan akses informasi politik dapat menyebabkan ketimpangan dalam partisipasi politik. Beberapa media mungkin memfokuskan perhatian mereka pada partai politik tertentu dan mengabaikan yang lain, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam proses politik. Persoalan atas idealisme media seringkali timbul bukan hanya berasal dari wartawan yang menyajikan berita yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik, tetapi keseimbangan media itu sendiri. Tidak jarang, berita yang tersaji hanya sesuai dengan kepentingan pemilik media. Kepemilikan media dapat mempengaruhi cara orang memikirkan dan menanggapi informasi yang mereka terima. Kepemilikan media yang kuat dapat memungkinkan pemiliknya untuk mengarsipkan, mengedit, dan menyaring informasi yang disampaikan. Ini memungkinkan pemilik media untuk mengendalikan cara informasi dipresentasikan dan menyaring informasi yang tidak disukai. Kepemilikan media juga dapat membuat orang lebih cenderung menerima informasi tertentu, meningkatkan sensitifitas terhadap informasi tertentu, dan mempengaruhi apa yang dianggap sebagai fakta. Kepemilikan media juga sering digunakan sebagai alat propaganda. Pemilik media dapat memilih untuk memfokuskan informasi tertentu dan menyoroti berita dan opini yang mendukung pandangan tertentu. Ini dapat menciptakan sebuah “echo chamber” di mana pandangan tertentu diulang tanpa tanggapan kritis. Ini dapat membantu menciptakan kesetiaan dalam komunitas tertentu yang menerima informasi tersebut, dan juga membantu membentuk pandangan yang lebih luas tentang isu tertentu. Ini juga dapat meningkatkan polarisasi politik dan membuat orang lebih konservatif dalam pandangan mereka. Di Indonesia sendiri, ada beberapa politisi pemilik media seperti; Surya Paloh, Erick Thohir, Aburizal Bakrie, Hary Tanoesoedibjo, Dahlan Iskan, Chairul Tanjung. Penetrasi Media Sosial Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari dan mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kehadiran media sosial memungkinkan kita untuk membuat koneksi dengan orang di seluruh dunia, menyebarkan informasi, serta membagikan gagasan dan pendapat. Hal ini telah menciptakan sebuah era baru yang disebut sebagai era media sosial. Era media sosial telah membuka pintu untuk pendekatan komunikasi yang berbeda. Kehadiran platform media sosial seperti youtube, twitter, facebook, dan instagram, whatsapp memberikan kemudahan serta tantangan di dunia politik. Penetrasi media sosial dalam politik telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini memungkinkan politisi untuk berinteraksi langsung dengan konstituen dan membuat kampanye yang efektif. Media sosial telah menjadi instrumen yang kuat untuk mempromosikan ide-ide politik dan membuat kampanye untuk berbagai kepentingan politik. Politikus dapat menggunakan media sosial sebagai alat untuk membuat kampanye yang lebih efektif dan menjangkau konstituennya. Dengan bantuan media sosial, mereka dapat membagikan informasi tentang program-program politik mereka melalui posting, iklan, dan berkomunikasi secara interaktif dengan konstituen. Media sosial juga memberikan kemampuan bagi politisi untuk mengumpulkan data tentang preferensi dan kebutuhan konstituen mereka, sehingga mereka dapat menyajikan konten yang sesuai dengan harapan mereka. Disisi lain, Penetrasi media sosial dalam dunia politik memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat. Berkat media sosial, informasi dapat disebarkan dengan lebih cepat dan luas, membuat orang lebih mudah terlibat dalam politik dan memperkuat partisipasi mereka. Pendapat masyarakat tentang berbagai isu politik dapat dengan mudah disampaikan dan didengar oleh publik, menciptakan kesadaran politik dan membantu mempercepat perubahan. Media sosial juga menjadi platform bagi masyarakat untuk berhubungan langsung dengan para politisi dan memengaruhi mereka dengan suara mereka. Partisipasi masyarakat dalam diskusi dan debat politik juga semakin mudah dan efektif, memberikan suara mereka dan membuat dorongan untuk perubahan yang lebih besar. Dengan demikian, media sosial membuka jalan bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam politik dan membantu membentuk demokrasi yang lebih berfungsi dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Menjaga Stabilitas Demokrasi Di Indonesia, sebagai negara demokrasi, keadilan dan transparansi dalam media sangat penting bagi proses politik. Pemerintah harus memastikan bahwa media memainkan peran yang benar dalam menyediakan informasi yang akurat dan menyebarkannya kepada masyarakat. Ini akan membantu membentuk keputusan politik yang didasarkan pada informasi yang valid dan adil. Semua pihak harus bekerja sama untuk menghormati hak asasi manusia, bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan membangun budaya yang menjamin kesetaraan hak dan kebebasan bagi semua warga negara. Pemerintah harus menghormati hak warga negara untuk menikmati hak asasi mereka, termasuk hak untuk berbicara bebas, berekspresi, dan menyampaikan pandangan mereka tanpa takut. Selain itu, pemerintah harus menjamin kebebasan pers dan menghormati prinsip-prinsip peraturan yang berhubungan dengan hak asasi warga negara. Dalam menjamin demokrasi, media harus bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang, dan juga menghindari berita yang menyesatkan dan menyebarkan informasi yang tidak benar. Para pendukung demokrasi harus memastikan bahwa media adalah alat untuk menyebarkan informasi yang akurat dan berimbang, dan bukan alat untuk mempromosikan agenda tertentu. Untuk memastikan bahwa informasi yang didapat oleh masyarakat adalah benar dan dapat dipercaya, peran aktif dan kritis dari masyarakat sangat penting. Masyarakat harus memainkan peran mereka sebagai pemegang kebenaran, dengan memverifikasi setiap informasi yang disampaikan oleh media dan berhati-hati terhadap berita-berita yang memiliki judul provokatif. Ini akan membantu mengurangi tersebarnya isu-isu hoax dan memastikan bahwa informasi yang didapat oleh masyarakat adalah akurat dan dapat diandalkan. Penulis : Shaqti Qhalbudien Yusuf (Anggota KPU Kab. Bone Bolango)