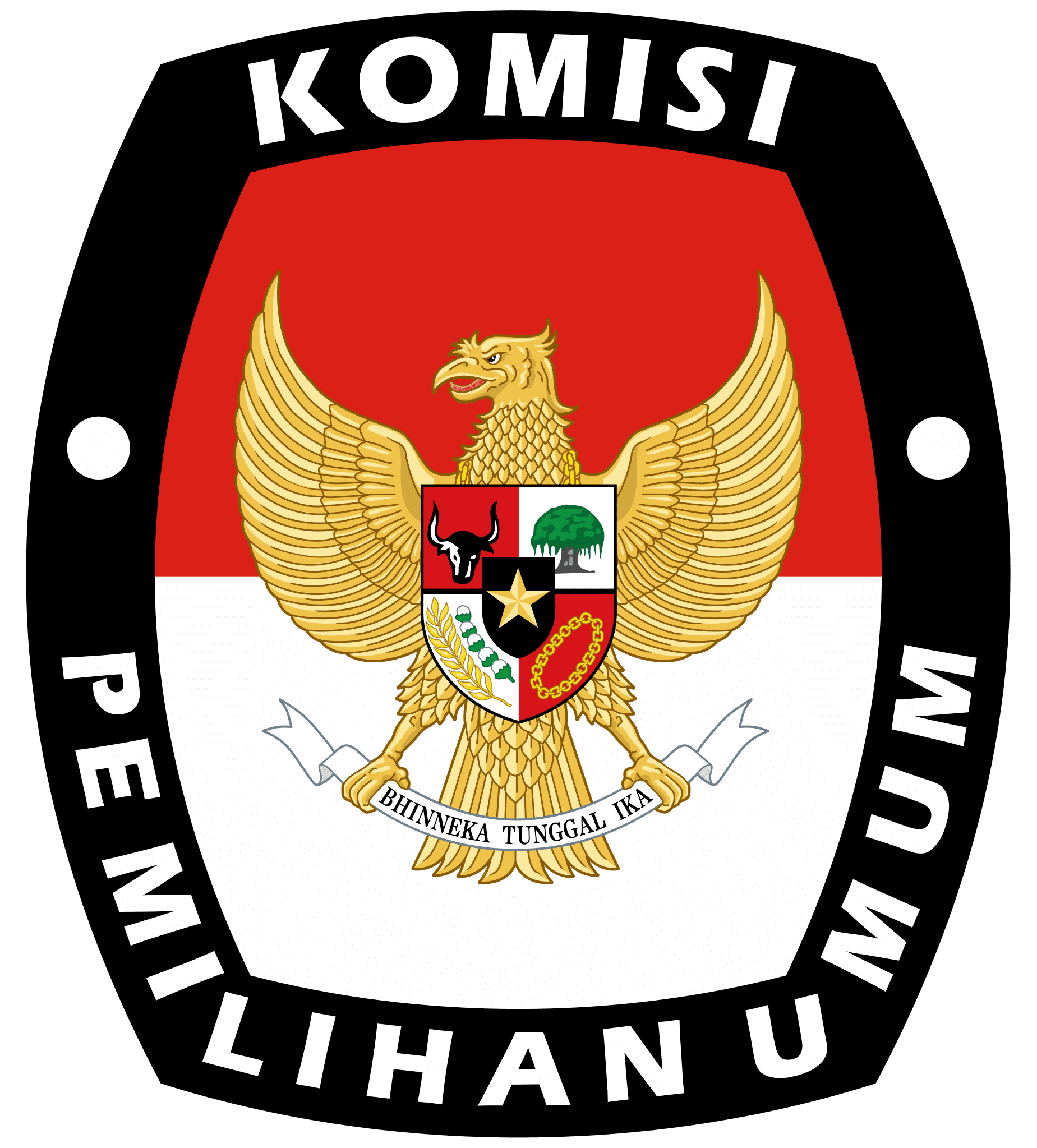DEMOKRASI EGALITER: PEREMPUAN DALAM PEMILU

Oleh : Shaqti Qhalbudien Yusuf (Anggota KPU Kab. Bone Bolango)
Dalam penyelenggaraan demokrasi, keterlibatan perempuan selalu menjadi perhatian penting. Perempuan sebagai kelompok masyarakat yang jumlahnya sekitar 50,3% sedikit lebih banyak dibanding laki-laki, memiliki hak yang sama untuk berperan sebagai pemilih, kandidat, maupun penyelenggara pemilu. Kita memahami betul bahwa tanpa keterlibatan penuh perempuan, kualitas demokrasi bangsa ini akan selalu timpang, karena separuh suara rakyat tak boleh hanya diperlakukan sebagai pelengkap.
Penerapan mekanisme zipper system dalam pencalonan legislatif, merupakan salah satu upaya untuk memastikan keterwakilan mereka dalam kontestasi politik.
Tujuannya jelas: memastikan perempuan tidak hanya hadir, tetapi juga memiliki peluang strategis untuk dipilih. Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kuota formal saja tidak cukup. Kita sering menyaksikan bagaimana kehadiran perempuan berhenti pada angka, sementara kapasitas, kompetensi, dan kontribusi strategis mereka belum sepenuhnya diberdayakan.
Padahal, di satu sisi, banyak perempuan memiliki kemampuan luar biasa dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan proses politik. Di sisi lain, akses, budaya, dan stigma sosial masih menjadi penghalang nyata bagi partisipasi penuh mereka. Kuota hadir sebagai pemicu, tetapi keterlibatan substantif membutuhkan pendidikan, persiapan, dan pengakuan nyata atas kapasitas yang mereka miliki.
Tulisan ini menelusuri perjalanan perempuan dalam demokrasi, menyoroti tantangan dan peluang mereka sebagai pemilih, kandidat, dan penyelenggara pemilu. Kita ingin melihat lebih jauh bahwa memberdayakan perempuan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi bangsa secara keseluruhan.
Kuota vs Kesiapan: Paradoks Zipper System
Realitas demokrasi kita menunjukkan, kehadiran perempuan seringkali dipastikan lewat instrumen formal, salah satunya zipper system. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan diperinci dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023, yang mewajibkan partai politik menempatkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif dengan pola penyusunan bergantian. Secara normatif, aturan ini tampak sebagai langkah progresif yang menjanjikan kesetaraan.
Namun, praktik di lapangan sering kali berkata lain. Kuota yang dimaksudkan untuk membuka akses politik justru berakhir menjadi formalitas angka semata. Kita kerap menyaksikan perempuan masuk daftar calon bukan karena kesiapan atau kapasitas, melainkan sekadar untuk memenuhi syarat hukum. Dalam kondisi seperti ini, meritokrasi terkikis, digantikan simbolisme yang mereduksi kualitas demokrasi.
Paradoks ini makin mencolok jika kita melihat fakta demografi: jumlah perempuan di Indonesia sedikit lebih banyak daripada laki-laki. Secara logis, ketersediaan kader perempuan seharusnya tidak menjadi masalah. Namun kenyataan menunjukkan sebaliknya, bahwa “stok” kader yang benar-benar siap tampil tetap langka. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah persoalannya ada pada kapasitas perempuan yang belum optimal, atau pada akses politik yang masih tertutup rapat oleh struktur patriarki?
Seharusnya, batas minimal dalam zipper system menjadi pemicu, bukan pengganti persiapan nyata. Tanpa penguatan kapasitas, kuota hanya melahirkan ilusi representasi: perempuan memang hadir secara formal, tetapi kualitas kepemimpinan mereka tidak terjamin. Politik pun berubah menjadi panggung simbolik, bukan arena meritokrasi.
Refleksi ini menuntut keseriusan kita bersama: jika demokrasi ingin benar-benar inklusif, keterwakilan perempuan tidak cukup diukur dari kuota semata. Yang
dibutuhkan adalah kesiapan, kapasitas, dan keberanian untuk berkontribusi secara nyata. Zipper system hanyalah alat; tanpa pemberdayaan substantif, ia akan tetap menjadi angka kosong yang terlihat di permukaan, kehilangan makna dalam praktik.
Budaya Patriarki dan Stigma Sosial
Jika kuota membuka pintu formal, budaya patriarki dan stigma sosial sering kali menjadi kunci yang menutupinya kembali. Kita masih hidup dalam warisan budaya yang membatasi peran perempuan pada ruang domestik, seolah-olah ruang publik bukanlah milik mereka. Norma yang tampak wajar ini, tanpa kita sadari, menimbulkan keraguan, pesimisme, dan rasa takut bagi banyak perempuan untuk tampil di panggung politik.
Ironisnya, ketika kesempatan benar-benar diberikan, perempuan berulang kali membuktikan kapasitasnya. Sejarah menjadi saksi: Nusaibah binti Ka’ab (Ummu
Imarah) tampil gagah dalam Perang Uhud, melindungi Rasulullah SAW dengan keberanian luar biasa. Rufaidah al-Aslamiyah membangun sistem medis pertama di Madinah dengan dedikasi yang menyelamatkan banyak nyawa. Di tanah air, sosok seperti Cut Nyak Dien, R.A. Kartini, dan Dewi Sartika menunjukkan bahwa perempuan bukan sekadar pelengkap, melainkan penggerak sejarah bangsa.
Namun, di panggung politik modern, stigma sosial masih kerap mengerdilkan peran perempuan. Mereka diharapkan hadir, tetapi dengan syarat: jangan terlalu vokal, jangan terlalu dominan, jangan mengganggu “tatanan”. Akibatnya, banyak perempuan ditempatkan hanya untuk memenuhi angka, bukan sebagai peserta yang disiapkan dengan serius. Kuota yang semula dimaksudkan sebagai pemicu representasi, ketika bersinggungan dengan budaya patriarki, justru berisiko berubah menjadi simbol kosong tanpa substansi.
Kita perlu jujur mengakui paradoks ini: kemampuan perempuan sudah terbukti sepanjang sejarah, tetapi budaya modern masih mengulang pola lama yang
mengekang. Demokrasi yang sehat tidak cukup hanya memberi ruang formal; ia harus membongkar belenggu budaya yang menghalangi perempuan untuk benar-benar berdaya.
Transisi ini membawa kita pada pertanyaan berikutnya: jika perempuan sudah berkali-kali membuktikan diri, lalu bagaimana mereka bisa berperan nyata dalam politik dan ruang publik hari ini?. Dari belenggu budaya patriarki, kita belajar satu hal penting: keterbatasan akses bukanlah cerminan keterbatasan kemampuan perempuan. Saat ruang benar-benar terbuka, terlihat jelas bagaimana perempuan mampu mengambil peran nyata dalam politik maupun ruang publik.
Kapasitas Perempuan dalam Politik dan Ruang Publik
Di panggung demokrasi modern, banyak perempuan hadir bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai penggerak perubahan. Kita bisa menyaksikan perempuan memimpin lembaga penyelenggara pemilu di berbagai daerah, mengelola proses yang rumit dengan ketegasan dan integritas. Kita juga melihat perempuan yang berani maju sebagai kandidat legislatif, kepala daerah, atau pemimpin partai politik, memperjuangkan aspirasi yang sering kali diabaikan oleh sistem politik yang didominasi laki-laki.
Kapasitas mereka bukan sekadar formalitas kuota. Cara berpikir relasional, empati, dan naluri keibuan yang khas menghadirkan perspektif berbeda dalam pengambilan keputusan politik. Dalam banyak kasus, hal ini menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, berpihak pada kelompok rentan, serta memperkuat keadilan sosial. Kita bisa melihatnya pada kebijakan-kebijakan yang menekankan perlindungan anak, kesejahteraan keluarga, kesehatan masyarakat, dan pendidikan, merupakan isu-isu yang sering kali diperjuangkan dengan lebih serius oleh legislator perempuan.
Namun, paradoks tetap mengintai. Zipper system yang semula dimaksudkan sebagai pintu masuk sering diterjemahkan sebatas angka, bukan sebagai ruang untuk menumbuhkan kapasitas kepemimpinan. Kita sering menyaksikan perempuan didorong maju tanpa persiapan memadai, sehingga meritokrasi tersisih oleh
simbolisme. Padahal, perempuan yang benar-benar disiapkan mampu menyeimbangkan kepemimpinan, memperkuat kualitas keputusan politik, dan menghadirkan legitimasi demokrasi yang lebih kokoh.
Sejarah dan fakta modern sama-sama memberi kita pelajaran: ketika perempuan diberi ruang, kesempatan, dan pengakuan, mereka bukan sekadar ikut serta,
melainkan hadir sebagai kekuatan strategis yang menentukan arah. Kepemimpinan, visi politik, dan integritas sejatinya tidak pernah soal gender, melainkan soal kapasitas dan kesiapan.
Dari sini kita sampai pada kenyataan berikutnya: perempuan tidak hanya hadir sebagai pemimpin atau kandidat, tetapi juga sebagai pemilih aktif yang memegang pengaruh strategis dalam menentukan kualitas demokrasi.
Perempuan sebagai Pemilih dan Penggerak Demokrasi
Partisipasi perempuan dalam demokrasi tidak berhenti pada keterwakilan di daftar calon. Lebih dari itu, mereka adalah pemilih aktif yang menentukan arah politik bangsa. Jumlah perempuan yang sedikit lebih besar dibanding laki-laki justru kontras dengan realitas politik: suara mereka sering diperlakukan sebagai tambahan belaka, padahal sejatinya menjadi penentu legitimasi kepemimpinan dan kualitas demokrasi.
Kita tahu bahwa perempuan tidak hadir sebagai massa pasif. Mereka adalah pembentuk opini, penggerak komunitas, dan penentu hasil pemilu. Dalam banyak
peristiwa, suara perempuan menjadi penentu kemenangan kandidat, bahkan mengubah peta politik. Sayangnya, peran besar ini masih sering dipandang sebelah mata. Perempuan dianggap hanya sebagai angka dalam statistik pemilih, padahal kontribusi mereka jauh lebih substansial.
Ketika perempuan diberdayakan untuk menggunakan hak pilihnya secara kritis, arah kebijakan publik pun ikut berubah. Kita bisa melihat bagaimana perempuan yang sadar akan hak politiknya cenderung mendorong isu-isu yang lebih inklusif: pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan kesejahteraan keluarga. Isu-isu yang sering dipinggirkan dalam wacana politik maskulin justru mendapat ruang ketika suara perempuan diperhitungkan dengan serius.
Namun, tantangan besar tetap ada. Budaya patriarki dan stigma sosial masih membuat banyak perempuan ragu untuk bersuara kritis atau terlibat aktif dalam proses politik. Kita sering menjumpai bagaimana perempuan yang berani menyampaikan pandangan dianggap “kurang pantas,” sementara yang diam
dianggap sesuai dengan norma. Paradoks ini membuat partisipasi perempuan seolah dibatasi oleh aturan tak tertulis yang membungkam potensi mereka.
Refleksi ini membawa kita pada pemahaman penting: perempuan sebagai pemilih bukanlah sekadar elemen statistik. Mereka adalah kekuatan pengubah arah demokrasi, penentu kualitas kepemimpinan, dan penyeimbang dalam keputusan politik. Jika suara perempuan dihitung, didengar, dan diterjemahkan ke dalam kebijakan, maka demokrasi menjadi lebih adil, lebih bermakna, dan lebih inklusif.
Transisi ini mengantarkan kita pada dimensi berikutnya: perempuan tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai kandidat dan penyelenggara, posisi di mana mereka ikut menentukan jalannya demokrasi dari dalam.
Perempuan sebagai Kandidat dan Penyelenggara
Dari bilik suara, perjalanan perempuan dalam demokrasi berlanjut ke panggung yang lebih menantang: pencalonan politik dan penyelenggaraan pemilu. Jika sebagai pemilih perempuan memegang kendali legitimasi, maka sebagai kandidat dan penyelenggara mereka adalah arsitek yang membentuk wajah demokrasi itu sendiri.
Sebagai kandidat, perempuan membawa nuansa baru dalam politik. Mereka menghadirkan perspektif yang lebih inklusif, keberpihakan pada kelompok rentan,
serta kepekaan sosial yang lahir dari pengalaman hidup sehari-hari. Kita dapat melihat bahwa ketika perempuan menduduki kursi legislatif atau jabatan publik, kebijakan yang lahir lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Dengan kata lain, kehadiran mereka memperluas cakrawala politik yang kerap sempit terjebak pada perebutan kekuasaan semata.
Namun, jalan menuju kursi politik tidak pernah mudah. Perempuan sering menghadapi hambatan ganda: sistem politik yang belum ramah gender, serta stigma sosial yang terus melekat. Mereka dipertanyakan bukan pada gagasan atau program, melainkan pada status keluarga, peran domestik, bahkan penampilan fisik. Politik menjadi arena yang lebih berat, karena selain berkompetisi dengan lawan politik, mereka juga harus melawan stereotip dan prasangka yang mengakar.
Sebagai penyelenggara pemilu, perempuan memegang peran strategis yang tak kalah penting. Mereka adalah penjaga integritas proses demokrasi, memastikan
setiap tahapan berjalan jujur, transparan, dan adil. Kehadiran mereka bukan hanya menambah keragaman perspektif, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Kita sering melihat bagaimana penyelenggara perempuan menunjukkan ketelitian, ketegasan, dan ketahanan menghadapi tekanan politik, serta kepekaan terhadap potensi diskriminasi.
Sayangnya, di banyak tempat, kehadiran perempuan dalam posisi ini masih direduksi menjadi sekadar pemenuhan kuota. Bukan sedikit perempuan yang ditempatkan distruktur penyelenggara atau daftar kandidat hanya untuk memenuhi aturan formal, tanpa benar-benar diberdayakan. Padahal meritokrasi menuntut sebaliknya: perempuan yang kompeten, berintegritas, dan visioner harus diberi ruang untuk
memimpin, bukan sekadar menghiasi struktur.
Paradoksnya jelas: perempuan dituntut hadir, tetapi tidak selalu diberi ruang untuk berdaya. Demokrasi yang berhenti pada angka tidak akan pernah melahirkan kualitas. Hanya ketika perempuan dipersiapkan, didukung, dan diakui kapasitasnya, mereka dapat menjadi pilar yang memperkuat legitimasi, profesionalisme, dan integritas demokrasi.
Dari pemilih hingga penyelenggara, perjalanan perempuan dalam demokrasi menyingkap satu pesan penting: keterwakilan formal hanyalah permulaan. Yang
menentukan adalah kesediaan demokrasi untuk menerima keterlibatan substantif mereka, yaitu sebagai penggerak perubahan, penyeimbang kepemimpinan, dan penjaga kualitas bangsa.
Inklusivitas dan Keadilan dalam Demokrasi
Perjalanan panjang membicarakan perempuan sebagai pemilih, kandidat, dan penyelenggara membawa kita pada satu kesadaran: demokrasi yang sehat tidak
cukup hanya dihitung dari kuota. Kehadiran perempuan dalam politik bukanlah soal angka, melainkan soal kualitas keterlibatan, kesiapan, dan kapasitas nyata yang mereka hadirkan.
Kuota 30% dalam zipper system memang langkah progresif, tetapi jika berhenti menjadi formalitas, ia hanya berubah menjadi simbol kosong. Demokrasi yang
bergantung pada angka semata akan kehilangan substansinya, karena meritokrasi tergeser oleh simbolisme. Kuota seharusnya menjadi pemicu, bukan pengganti; jembatan menuju keterlibatan sejati, bukan sekadar tanda di atas kertas.
Lebih dari itu, kita diingatkan bahwa budaya patriarki dan stigma sosial adalah penghalang terbesar yang masih menahan perempuan. Demokrasi yang hanya
membuka ruang di regulasi, tetapi menutup pintu di lapangan, sejatinya adalah demokrasi pincang. Kita tidak bisa terus membiarkan perempuan dilihat sebagai
pelengkap; mereka adalah penentu arah kebijakan, penjaga integritas pemilu, dan penggerak legitimasi politik.
Sejarah dan fakta modern sama-sama telah berbicara lantang: ketika perempuan diberi ruang, mereka membuktikan kapasitas strategisnya. Mereka menghadirkan perspektif inklusif, memperjuangkan kepentingan publik yang lebih luas, dan menyeimbangkan kepemimpinan yang sering terjebak dalam perebutan kekuasaan.
Karena itu, memberdayakan perempuan bukan sekadar kewajiban moral, melainkan investasi kualitas bagi masa depan bangsa. Demokrasi yang egaliter hanya mungkin terwujud jika perempuan diperlakukan sebagai subjek yang berdaya, disiapkan dengan serius, dan dihargai kapasitasnya.
Demokrasi yang menutup pintu bagi perempuan bukanlah demokrasi yang sehat. Demokrasi yang memperkecil suara mereka bukanlah demokrasi yang bermartabat. Maka, jika kita sungguh-sungguh ingin membangun demokrasi yang kuat, legitimate, dan adil, tidak ada jalan lain kecuali memastikan perempuan hadir bukan sebagai angka, melainkan sebagai kekuatan yang hidup, menggerakkan, dan menentukan arah masa depan politik Indonesia.
Salam takzim,
Shaqti Qhalbudien Yusuf
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
KPU Kab. Bone Bolango
![]()
![]()
![]()
![]()